 |
| Candi Borobudur, photo by Postlicious |
Para arkeolog Indonesia membedah peninggalan masa
lalu. Tak sebatas menggali, tapi membuka tabir masyarakat dan sistem di zaman itu
sebagai warisan budaya bangsa.
Oleh M. Tahir Saleh
MASIH terekam dalam benak
Profesor Mundardjito betapa sulit merestorasi Candi Borobudur di Magelang, Jawa
Timur, sekitar 34 tahun silam. Ketika itu, Guru Besar Arkeologi Universitas
Indonesia (UI) ini ikut membantu pemugaran candi
Buddha terbesar di dunia ini.
Candi peninggalan pemerintahan
Syailendra abad kesembilan itu dibentuk oleh sekitar 2 juta blok batu andesit. Tim
memeriksa sana-sini, mencari tahu dari mana jutaan batu itu
diambil. Dengan analisis struktur, bentuk, kekerasan, dan kepadatan
yang mirip, interpretasi didapat bahwa batuan itu berasal dari Kali Blongkeng.
Pertanyaanya: bagaimana jutaan batu itu dibawa ke Borobudur
dengan jarak berkilo-kilometer, sementara belum ada mesin otomotif zaman itu? Setelah tak menemukan
kulit batu di Borobudur, interpretasi lagi-lagi diperoleh: batu-batu pembentuk
candi ternyata dibentuk kotak di Blongkeng supaya efisien dibawa dengan roda
kereta saat itu. Kesimpulan alat transportasi ini dikuatkan dengan historical data dari relief-relief Candi
Borobudur.
“Kami menggali batu, enggak ketemu kulit batu, berarti batu yang dibawa ke Borobudur itu
dari sana [Blongkeng] sudah dibentuk kotak, bukan bulat. Itu perilakunya,” terang Mundardjito, Selasa pekan
lalu (21/1).
 |
| Sang profesor di Salihara, photo by Salihara, Flickr |
Arkeolog senior yang sudah malang
melintang meneliti—mulai dari situs Kerajaan
Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, hingga Candi Muaro Jambi—itu memberikan kuliah umum bertema ‘Bagaimana Arkeolog
Berpikir dan Bekerja’ di Serambi Salihara, Jakarta, 21 Januari lalu. Sejumlah artikel dan buku
mengenai arkeologi pun ditulisnya, seperti Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem dan Teknologi (2009) dan Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Masa
Hindu-Buddha di Daerah Yogyakarta (2002).
Baginya pekerjaan arkeolog semacam
detektif masa lalu. Layaknya ahli forensik, arkeolog menggali, menemukan, dan
membuktikan. Aktivitas arkeolog sangat berpedoman pada disiplin ilmu
dan logika, bukan mitos, apalagi rumor. Mereka tak berdiri di atas ‘menara
gading’, tapi berupaya menemukan peradaban masa lampau sambil
menemukan bukti kelahiran dan keruntuhan warisan budaya itu.
Beberapa analisis yang mendukung
kerja arkeolog di antaranya analisis bentuk, lalu analisis konteks bagaimana
menghubungkan benda temuan dengan temuan lain. Gerabah, katanya, merupakan benda yang paling sering ditemukan karena dianggap ‘remeh’
dan ditinggalkan penduduk. Tapi, benda ini
penting bagi arkeolog. Analisis lain,
yakni etnografi dengan fokus pada tempat lain dengan keterkaitan temuan yang
sama sebagai penambah data. Lalu, analisis
eksperimental yang juga melibatkan spesialis bukan arkeolog.
Sejumlah penemuan bukan sebatas
membuka tabir budaya, kesenian, dan perekonomian masa lalu, melainkan bagaimana
penemuan itu bermanfaat bagi masa kini, termasuk teknologi. “Ini tampak saat meneliti Majapahit. Sistem pengairan
dengan kanal-kanal yang begitu luar biasa, air dialirkan ke pusat kota dengan
sangat baik.”
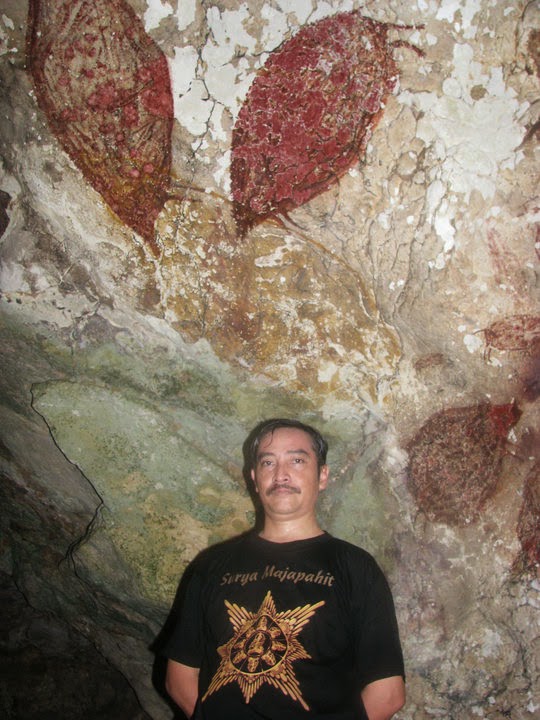 |
| Cecep Eka di Sulsel, photo by Facebook |
Cecep Eka Permana, dosen
Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, menjelaskan perbedaan disiplin
arkeologi dengan bidang lain yakni ekskavasi atau penggalian. Artinya bukan
menggali gorong-gorong atau gali asal-asalan. Sebelum menggali, pengumpulan data
melalui survei wajib dilakukan. Entah itu lewat satelit untuk melihat anomali
suatu daerah atau dengan sonar (mendeteksi di bawah laut dengan gelombang
suara). Kemudian ditambah dengan kajian kepustakaan.
Arkeolog—yang selalu bekerja
dalam tim—pun harus mengecek lapangan untuk membuat test pit atau kotak uji sebelum meletakkan kotak ekskavasi asli. Setelah itu barulah
menempatkan kotak ekskavasi. Terdapat empat patok membentuk kotak ini, biasanya untuk latihan mahasiswa, luasnya
hanya 2 x 2 meter. Di dalam kotak, dibuat kotak lagi. Di
kotak gali inilah arkeolog bekerja.
Rumus awal ini perlu karena, dengan berpedoman pada kotak galian ini, bisa tampak lapisan tanah dan temuannya. Dalam hukum superposisi, lapisan makin ke bawah, makin
tua. Kalau ada temuan di luar kotak, dibuatkan kotak lagi dan seterusnya. “Kalau
salah melihat dan mencatat, temuan bisa tercampur, padahal berbeda lapisan,”
kata Cecep.
Jangan salah, ketika menggali pun
arkeolog memakai alat khusus yang biasa menjadi senjata
tukang bangunan. “Enggak boleh pakai
cangkul, tapi sendok semen, pacul kecil, petel, kete’ [alat dempul],” kata Cecep yang pernah meneliti gua-gua
prasejarah di Pangkep, Sulawesi Selatan ini.
Namun, kerap terjadi informasi berasal dari laporan
penduduk. Penggalian candi-candi di Batujaya, Karawang, Jawa Barat, pada 1984
adalah hasil informasi masyarakat sekitar. Di kawasan ini, ditemukan candi-candi
peninggalan abad keempat sampai abad ketujuh peninggalan Kerajaan Tarumanegara. “Harus hati-hati. Sulit karena lokasinya di tengah
sawah, berjibaku dengan air yang kerap masuk ke lobang galian.”
Kehati-hatian itu juga dialami
Mundardjito. Saat abu vulkanik Gunung Merapi menutupi Borobudur, bersama
sukarelawan, dia memakai bilah bambu untuk membersihkan abu yang menutupi pori-pori
batu supaya batu bisa bernafas. “Itu sekeliling Borobudur. Bayangin aja
pakai bambu, satu-satu dicongkel, saking cintanya,”
Meski arkeolog punya tugas mulia, Mundardjito berharap masyarakat memiliki pemahaman soal cagar budaya. Ini penting karena masyarakat hidup di tengah-tengah wilayah yang bisa saja dulunya menyimpan harta kebudayaaan. Sebelum restorasi Bodobudur, dia teringat kejadian yang memiriskan hati. “Ada warga menumbuk padi di batu, pas dibuka, busyet dah stupa. Lalu batu di kamar mandi, begitu dilihat, wah ini relief. Saat itu juga kami ganti dengan batu lain, disebar ke masyarakat.”
Meski arkeolog punya tugas mulia, Mundardjito berharap masyarakat memiliki pemahaman soal cagar budaya. Ini penting karena masyarakat hidup di tengah-tengah wilayah yang bisa saja dulunya menyimpan harta kebudayaaan. Sebelum restorasi Bodobudur, dia teringat kejadian yang memiriskan hati. “Ada warga menumbuk padi di batu, pas dibuka, busyet dah stupa. Lalu batu di kamar mandi, begitu dilihat, wah ini relief. Saat itu juga kami ganti dengan batu lain, disebar ke masyarakat.”
Dari sisi pemerintah, kepedulian sudah ada, tapi belum maksimal. Dia ingat suatu hari ke
Istana Negara untuk melihat bendera pusaka hasil jahitan istri mendiang Presiden
Soekarno, Fatmawati. Dia langsung kaget
saat melihat pengamanan ‘pusaka tak ternilai’ itu seadanya saja—dengan CCTV tanpa alarm. Beda jauh dengan China yang menerapkan pengamanan tingkat tinggi untuk melindungi warisan
budaya.
Dia pun teringat ucapan almarhum
Soekmono, salah satu arkeolog Indonesia yang pernah memimpin
proyek pemugaran Candi Borobudur (1971-1983). Pundak Mundardjito ditepuk dari belakang dan Soekmono
bilang kepadanya: “Jangan sembarang menggali, kalau belum tahu gimana program pelestariannya.”
Tulisan ini terbit di majalah
Bloomberg Businessweek Indonesia, Senin 3 Februari 2014.
Words: 877

.jpg)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar